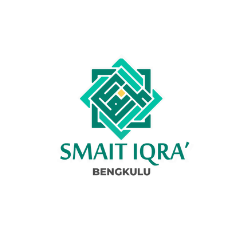Cahaya di Ujung Pagi
Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah dan perbukitan hijau, hiduplah seorang Ibu bernama Bu Rini. Sejak suaminya meninggal lima tahun lalu karena kecelakaan kerja di kota, Bu Rini membesarkan anak semata wayangnya, Dimas, seorang diri. Kehidupan mereka sederhana, bahkan cenderung pas-pasan. Namun, satu hal yang selalu diperjuangkan Bu Rini adalah pendidikan anaknya. Baginya, pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan yang telah lama membelenggu keluarganya.
Setiap hari, sebelum fajar menyingsing, Bu Rini sudah bangun dan bersiap. Ia menjajakan sayur mayur keliling kampung dengan sepeda tuanya. Sepeda itu peninggalan almarhum suaminya, yang kini setia menemaninya menyusuri jalan-jalan desa. Dengan dua keranjang besar berisi sayur, tahu, tempe, dan bumbu dapur, ia mengayuh perlahan dari rumah ke rumah. Tak peduli hujan atau panas, lelah atau sakit, Bu Rini tetap berjualan. Semua demi Dimas.
Dimas adalah anak yang cerdas. Sejak duduk di bangku SD, ia selalu mendapat peringkat teratas di kelas. Namun, memasuki SMP, ia mulai merasa minder. Beberapa temannya berasal dari keluarga berada, datang ke sekolah dengan sepeda baru, membawa bekal yang berlimpah, dan seringkali membicarakan hal-hal yang tidak bisa ia mengerti.
"Bu, aku gak mau sekolah tinggi-tinggi. Lagian, kita gak punya uang," kata Dimas suatu malam, saat mereka sedang makan malam seadanya: nasi, tempe goreng, dan sambal.
Bu Rini menatap anaknya lama, lalu meletakkan sendok. "Nak, Ibu memang tak punya banyak. Tapi selama Ibu masih bisa mengayuh sepeda ini, kamu harus sekolah. Ilmu itu cahaya, Mas. Tanpa itu, kita tetap di tempat yang gelap."
Ucapan itu tertanam kuat di hati Dimas. Sejak saat itu, ia belajar lebih giat. Ia mulai meminjam buku dari perpustakaan sekolah dan bahkan sering membantu teman-temannya belajar, meski kadang harus menahan lapar karena bekalnya habis sejak pagi.
Sementara itu, Bu Rini makin keras bekerja. Selain berjualan keliling, ia juga menerima pesanan sayur dari warung-warung kecil di desa. Malam harinya, ia menyiangi sayur, mencuci beras, dan menyiapkan dagangan untuk esok. Tangannya kasar dan penuh kapalan, punggungnya sering nyeri karena terlalu sering membungkuk. Tapi ia tak pernah mengeluh.
Suatu ketika, sekolah mengadakan lomba pidato antar-SMP se-kabupaten. Dimas diminta mewakili sekolahnya. Ia sempat ragu, takut tidak punya pakaian yang layak. Tapi Bu Rini meminjam baju pada tetangga, menyetrikanya dengan rapi, dan menyemangati Dimas dengan senyum terbaiknya.
"Anggap saja kamu pidato di depan Ibu, Nak. Ceritakan tentang impianmu," katanya sambil mengusap rambut anaknya.
Dimas pun tampil dengan percaya diri dan membawakan pidato berjudul Pendidikan adalah Harapan. Ia bercerita tentang ibunya yang tak kenal lelah demi sekolahnya. Di akhir pidato, ia berkata, "Saya ingin menjadi orang yang bisa membuat ibu saya berhenti mengayuh sepeda di pagi hari. Saya ingin menjadi cahaya bagi beliau, sebagaimana beliau menjadi cahaya bagi saya."
Ruangan hening. Para juri terdiam, beberapa penonton meneteskan air mata. Dimas memenangkan lomba itu dan mendapat beasiswa untuk melanjutkan SMA di kota.
Hari itu, Bu Rini menjemput Dimas dengan sepeda tuanya seperti biasa, tapi hatinya terasa ringan seperti terbang. Ia memeluk anaknya erat, tangis haru mengalir tanpa bisa ia tahan.
"Ibu bangga sekali sama kamu, Mas..."
Sejak pindah ke kota, Dimas tinggal di asrama dan jarang pulang. Tapi setiap surat yang ia kirim selalu diawali dengan, Bu, terima kasih sudah menjadi pelita dalam hidupku.
Tahun demi tahun berlalu. Dimas melanjutkan kuliah di universitas negeri ternama, kembali dengan beasiswa penuh. Ia mengambil jurusan pendidikan, ingin menjadi guru agar bisa membantu anak-anak lain yang bernasib serupa dengannya.
Sementara itu, Bu Rini mulai berjualan dari rumah. Usianya yang kian senja membuatnya tak kuat lagi mengayuh sepeda sejauh dulu. Tapi ia tetap sibuk, menyiapkan pesanan warga yang kini mulai mengenalnya sebagai "ibunya Dimas, si juara kampung".
Hari itu, langit desa cerah. Warga berkumpul di balai desa, menghadiri acara pelantikan kepala sekolah baru di SMP mereka. Betapa terkejutnya semua orang saat melihat Dimas, kini seorang pria muda berjas rapi, melangkah naik ke panggung.
"Saya kembali ke desa ini bukan hanya sebagai guru, tapi sebagai anak dari seorang ibu luar biasa yang mengajarkan arti perjuangan. Semua ini saya persembahkan untuk Ibu Rini," ucapnya dengan suara bergetar.
Bu Rini, yang duduk di barisan depan, meneteskan air mata bahagia. Ia tak menyangka anak yang dulu dituntunnya belajar membaca kini menjadi guru, menjadi teladan.
Setelah acara selesai, Dimas menghampiri ibunya. Ia menggenggam tangan tua itu, lalu menciuminya.
"Bu, sekarang Ibu bisa istirahat. Biar aku yang bekerja, Bu."
Bu Rini hanya tersenyum. "Ibu tidak lelah, Mas. Melihat kamu seperti ini, semua rasa sakit Ibu hilang."
Dan saat senja turun, Bu Rini duduk di teras rumahnya, menatap langit dengan tenang. Dalam hatinya, ia tahu bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Ia telah menerangi jalan anaknya dengan cahaya cinta dan pengorbanan. Kini, cahaya itu telah menjadi terang bagi banyak orang lainnya.
Penulis : Fidya Hulwani Putri
Editor : Gunawan A